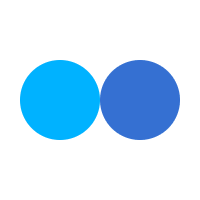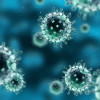1. Tobin MJ, Laghi F, Jubran A. Why COVID-19 silent hypoxemia is baffling to physicians. Am J Respir Crit Care Med. 2020;202(3):356-360. DOI: 10.1164/rccm.202006-2157CP
2. Wei-jie G, Zheng-yi N, Yu H, et al. Clinical characteristics of Coronavirus disease 2019 in China. N Engl J Med. 2020;382:1708–1720. doi: 10.1056/NEJMoa2002032
3. Xie J, Covassin N, Fan Z, et al. Association between hypoxemia and mortality in patients with COVID-19. Mayo Clin Proc. 2020; 95(6):1138-1147 DOI:10.1016/l.mayocp.2020.04.006
4. Siddiqi HK, Mehra MR. COVID-19 illness in native and immunosuppressed states: a clinical-therapeutic staging proposal. J Heart Lung Transplant. 2020;39(5):405-407. DOI:10.1016/j.healun.2020.03.012
5. Gattinoni L, Chiumello D, Caironi P, Busana M, Romitti F, Brazzi L, et al. COVID-19 pneumonia : different respiratory treatment for different phenotypes ? Intensive Care Med. 2020;46(6): 1099-1102. DOI: 10.1007/s00134-020-06033-2. Epub 2020 Apr 14.
6. Dhont et al. The pathophysiology of “happy’ hypoxemia in COVID-19. Respiratory Research. 2020;21:198 DOI: https://doi.org/10.1186/s12931-020-01462-5
7. Archer SL, Sharp WW, Weir EK. Differentiating COVID-19 pneumonia from acute respiratory distress syndrome (ARDS) and high altitude pulmonary edema (HAPE): therapeutic implications. Circulation.2020;142(2):101-104. DOI: 10.1161/CIRCULATIONAHA.120.047915.Epub 2020 May 5.
8. Lang M, Som A, Mendoza DP, Flores EJ, Reid N, Carey D, et al. Hypoxaemia related to COVID-19: vascular and perfusion abnormalities on dual-energy CT. Lancet Infect Dis. 2020;S1473-3099(20)30367-4. DOI: 10.1016/S1473-3099(20)30367-4. Online ahead of print.
9. Ottestad W, Søvik S. COVID-19 patients with respiratory failure: what can we learn from aviation medicine? Br J Anaesth. 2020;125(3):e280-e281. DOI: 10.1016/j.bja.2020.04.012.
10. Kickbusch I, Leung G. Response to the emerging novel coronavirus outbreak. BMJ. 2020;368:m406.doi: 10.1136/bmj.m406.
11. Zhang H, Baker A. Recombinant human ACE2: acing out angiotensin II in ARDS therapy. Crit Care. 2017;21(1):305. Doi:10.1186/s1054-017-1882-z.
12. Tay MZ, Poh CM, Rénia L, MacAry PA, Ng LFP. The trinity of COVID-19: immunity, inflammation and intervention. Nat Rev Immunol. 2020;20(6):363-374. Doi: 10.1038/s41577-020-0311-8. Epub 2020 Apr 28.
13. Jia HP, Look DC, Shi L, Hickey M, Pewe L, Netland J, et al. ACE2 receptor expression and severe acute respiratory syndrome coronavirus infection depend on differentiation of human airway epithelia. J Virol. 2005;79(23):14614-21. Doi: 10.1128/JVI.79.23.14614-14621.2005.
14. Bikdeli B, et al. COVID- 19 and thrombotic or thromboembolic disease: implications for prevention, antithrombotic therapy, and follow-up. J Am Coll Cardiol. 2020;75(23):2950-2973. Doi: 10.106/j.jacc.2020.04.031. Epub 2020 Apr 17.
15. Guérin C, Matthay MA. Acute cor pulmonale and the acute respiratory distress syndrome. Intensive Care Med. 2016;42(5):934-936. Doi: 10.1007/s00134-015-4187-z. Epub 2016 jan 13.
16. Campbell CM, Kahwash R. Will complement inhibition be the new target in treating COVID-19 related systemic thrombosis? Circulation. 2020;141(22):1739-1741. Doi: 10.1161/CIRCULATIONAHA.120.047419. Epub 2020 Apr 9.
17. Zhang L, Yan X, Fan Q, Liu H, Liu X, Liu Z, et al. D-dimer levels on admission to predict in-hospital mortality in patients with Covid-19. J Thromb Haemost. 2020;18(6):1324-1329. Doi: 10.1111/jth.14859.
18. Wang J, Hajizadeh N, Moore EE, McIntyre RC, Moore PK, Veress LA, et al. Tissue plasminogen activator (tPA) treatment for COVID-19 associated acute respiratory distress syndrome (ARDS): a case series. J Thromb Haemost.2020;18(7):1752-1755. Doi: 10.1111/jth.14828. Epub 2020 may 11.
19. Luo W, Yu H, Gou J, Li X, Sun Y, Li J, et al. Clinical pathology of critical patient with novel coronavirus pneumonia (COVID-19): Pulmonary Fibrosis and Vascular Changes including Microthrombosis Formation. Preprints 2020:2020020407. doi:10.13140/RG.2.2.22934.29762.
20. Tian S, Hu W, Niu L, Liu H, Xu H, Xiao S-Y. Pulmonary pathology of earlyphase 2019 novel coronavirus (COVID-19) pneumonia in two patients with lung cancer. J Thorac Oncol. 2020;15(5):700–704. doi: 10.1016/j.jtho.2020.02.010. Epub 2020 Feb 28.
21. Mason RJ. Pathogenesis of COVID-19 from a cell biologic perspective. Eur Respir J. 2020;55(4):2000607. doi: 10.1183/13993003.0067-2020.
22. Xiaoneng Mo et al. Abnormal pulmonary function in COVID-19 patients at time of hospital discharge. Eur Respir J.2020; 55(6): 2001217. DOI: 10.1183/13993003.01217-2020.
23. Gonzalez-Duarte A, Norcliffe-kaufmann L. Is ‘happy hypoxia’ in COVID-19 a disorder of autonomic interoception? A hypothesis. Clin Auton Res.2020;30(4):331-333. DOI: 10.1007/s10286-020-00715-z.
24. Fung ML. Expressions of angiotensin and cytokine receptors in the paracrine signaling of the carotid body in hypoxia and sleep apnea. Respir Physiol Neurobiol 2015;209:6–12. DOI: 10.1016/j.resp.2014.09.014. Epub 2014 Oct 3.