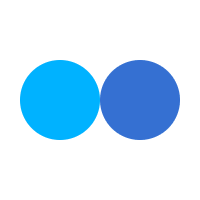Terdapat banyak pertanyaan tentang perbandingan imunitas alami dan imunitas yang diinduksi vaksin COVID-19. Mencapai herd immunity merupakan jalan keluar dari pandemi COVID-19. Beberapa uji klinis dan studi observasional telah mendemonstrasikan efikasi jangka pendek vaksin COVID-19 dalam mencegah COVID-19.
Namun, sudah terdapat beberapa laporan menurunnya kekebalan seiring bertambahnya waktu, sementara belum tersedia bukti ilmiah yang cukup untuk menilai proteksi jangka panjang dari vaksin COVID-19 maupun infeksi alami.
Pemahaman yang lebih baik tentang respons imun alami dan yang diinduksi vaksin diharapkan dapat berperan untuk mengembangkan vaksin yang efektif dan menentukan strategi penanggulangan pandemi COVID-19.[1]
Imunitas Alami
Seorang individu dapat terlindungi dari COVID-19 melalui kekebalan yang terbentuk akibat infeksi SARS-CoV-2 secara alami atau melalui vaksinasi COVID-19. Selain antibodi, imunitas terhadap SARS-CoV-2 juga ditentukan oleh faktor lain, seperti sel T CD4+, sel T CD8+, sel B memori.
Data yang ada menunjukkan bahwa antibodi penetralisir bertahan beberapa bulan dalam tubuh pasien COVID-19 dan berkurang seiring bertambahnya waktu. Sebuah studi meneliti 5.882 orang yang telah sembuh dari COVID-19 atau penyintas dan menemukan bahwa antibodi tetap ada dalam darah selama 5-7 bulan setelah onset untuk gejala ringan hingga sedang.
Tingkat kekebalan alami terhadap infeksi simtomatik COVID-19 telah ditemukan antara 93-100% selama 7 hingga 8 bulan.[3]
Berbagai penelitian menunjukkan bahwa respons imun yang melibatkan sel T dan B memori muncul setelah infeksi SARS-CoV-2. Namun, sistem imun masing-masing manusia merespons infeksi virus dengan cara yang berbeda, sehingga imunitas alami tidak bisa diandalkan secara penuh.[4]
Perlu dipahami juga mekanisme respons imun alami pada kasus asimtomatik, gejala ringan, sedang dan berat, pada tahap awal dan akhir infeksi cenderung menghasilkan respons imun yang berbeda. Pasien dengan gejala ringan atau asimtomatik akan memiliki tingkat antibodi yang lebih rendah daripada pasien dengan gejala berat. Hal ini akan memengaruhi imunitas di kemudian hari.[1]
Imunitas yang Diinduksi Vaksin COVID-19
Imunitas yang diinduksi vaksin mungkin berbeda dari imunitas alami akibat strategi immune-evasion oleh virus. Sebagian besar vaksin COVID-19 dirancang untuk memicu neutralizing antibodies (NAbs) terhadap spike protein SARS-CoV-2. Beberapa vaksin, termasuk vaksin mRNA, vektor adenovirus, protein subunit, dan virus inaktif, telah dilaporkan efektif dalam uji coba fase III dan telah disetujui untuk digunakan secara darurat di berbagai negara.[5]
Respons imun setelah vaksinasi diperkirakan lebih homogen, yang ditandai dengan terbentuknya reaktivitas sel T dan B pada penerima vaksin COVID-19. Hal ini membuat pembentukan imunitas setelah vaksinasi lebih dapat diprediksi dan diandalkan. Sebuah penelitian di London pada 50.000 partisipan melaporkan positifnya antibodi sebesar 96,4% setelah vaksinasi dosis pertama vaksin COVID-19 Pfizer atau AstraZeneca, dan 99,1% setelah dosis kedua.[4]
Membandingkan Imunitas Alami dengan Imunitas yang Diinduksi Vaksin
Sebuah penelitian retrospektif yang menggunakan database 2.500.000 pengguna jaminan kesehatan membagi responden menjadi 3 kelompok. Kelompok pertama adalah individu SARS-CoV-2 naif atau belum pernah terinfeksi COVID-19 tetapi sudah mendapat regimen lengkap vaksin COVID-19 Pfizer. Kelompok kedua adalah individu yang pernah terinfeksi tetapi belum divaksin. Kelompok ketiga adalah individu yang pernah terinfeksi dan mendapat 1 dosis vaksin.
Pada periode evaluasi, didapatkan 257 kasus infeksi SARS-CoV-2 varian Delta, di mana 238 kasus infeksi baru terjadi pada kelompok yang sudah divaksin dan 19 kasus reinfeksi pada kelompok penyintas COVID-19. Temuan ini menggambarkan bahwa risiko infeksi baru lebih tinggi secara signifikan daripada risiko reinfeksi.
Selama masa evaluasi, COVID-19 simtomatik dilaporkan terjadi pada 199 pasien, dengan 191 diantaranya berasal dari kelompok yang divaksin dan 8 pasien berasal dari kelompok penyintas. Gejala yang dilaporkan berupa demam, batuk, kesulitan bernapas, diare, hilangnya indra penciuman dan perasa, mialgia, malaise, nyeri kepala, dan nyeri tenggorokan. Peneliti menemukan bahwa risiko terjadinya COVID-19 simtomatik lebih tinggi 27,02 kali lipat pada infeksi baru daripada reinfeksi.[6]
Dilaporkan 9 kasus rawat inap, 8 diantaranya terjadi pada kelompok yang divaksin dan 1 kasus pada kelompok penyintas. Usia di atas 60 tahun merupakan faktor yang meningkatkan risiko rawat inap secara signifikan.
Risiko infeksi juga diperbandingkan antara kelompok penyintas COVID-19 yang belum divaksin dengan yang sudah mendapat vaksin dosis 1. Peneliti menemukan bahwa tren penurunan risiko reinfeksi pada kedua kelompok ini sama, meskipun tidak signifikan.[6]
Hasil penelitian ini mendemonstrasikan bahwa imunitas alami bertahan lebih lama dan memberikan proteksi lebih kuat terhadap infeksi SARS-CoV-2, keparahan gejala, dan rawat inap yang berkaitan dengan COVID-19, bila dibandingkan dengan imunitas yang diinduksi 2 dosis vaksin COVID-19 Pfizer terhadap varian Delta.
Strain dominan yang beredar di Israel saat penelitian ini berlangsung adalah COVID-19 varian Delta, sehingga proteksi jangka panjang vaksin yang dibandingkan dengan infeksi alami pada strain lain tidak dapat dipastikan. Selain itu, vaksin yang diteliti hanya lah vaksin COVID-19 Pfizer, sehingga efektivitas vaksin lain belum tercakup dalam penelitian ini.
Keterbatasan lain dari penelitian ini adalah kemungkinan bias yang berkaitan dengan skrining PCR yang tidak dilaksanakan sesuai dengan protokol, yang mungkin berimbas pada tidak terdeteksinya infeksi asimtomatik. Perlu dicatat juga bahwa studi berbasis populasi nyata ini masih berstatus prapublikasi, dan belum dilakukan peer-reviewed.[6]
Hybrid Immunity
Baru-baru ini terdapat istilah hybrid immunity, yaitu gabungan dari imunitas yang terbentuk secara alami dan imunitas yang dihasilkan atau diinduksi oleh vaksinasi. Kombinasi imunitas ini diperkirakan akan menghasilkan respons antibodi 25-100 kali lipat lebih tinggi, dengan mediasi sel B memori dan sel T CD4+. Sel B memori lah yang berperan dalam imunitas jangka panjang.
Antibodi penetralisir SARS-CoV-2 pada penyintas COVID-19 yang telah divaksin dinilai lebih tinggi 100 kali lipat dibandingkan dengan hanya imunitas alami atau imunitas yang diinduksi vaksin saja. Sebagian besar sel B memori menghasilkan antibodi yang mampu mengikat atau menetralisir berbagai varian SARS-CoV-2, dan kualitas sel B tersebut akan meningkat seiring waktu.[6]
Individu yang sebelumnya terinfeksi SARS-CoV-2 tampaknya mendapatkan perlindungan tambahan setelah mendapat regimen vaksinasi pascainfeksi. Perlindungan lebih yang diberikan oleh imunitas alami diduga terjadi akibat respons imun terhadap protein SARS-CoV-2 yang lebih luas dibandingkan respons imun yang dihasilkan oleh anti-spike protein yang dipicu vaksin.[6]
Pada penyintas COVID-19, peningkatan antibodi penetralisir pascavaksinasi akan merangsang sel B memori yang beragam dan berkualitas tinggi dibandingkan imunitas yang dihasilkan setelah infeksi awal.[3]
Kesimpulan
Kekebalan terhadap suatu patogen bisa didapatkan secara alamiah atau dengan diinduksi vaksin. Imunitas alami tampaknya memberikan proteksi yang bertahan lebih lama dan lebih kuat terhadap infeksi SARS-CoV-2, infeksi dengan gejala, dan tingkat rawat inap terkait COVID-19 dibandingkan dengan imunitas yang diinduksi vaksin.
Akan tetapi, respons imun tubuh terhadap suatu patogen merupakan rangkaian proses yang kompleks dan masih belum dapat dipahami seutuhnya. Masih diperlukan studi lebih lanjut mengenai imunitas terhadap COVID-19, termasuk imunitas jangka panjang yang dihasilkan vaksin COVID-19. Analisis terhadap hal ini akan bermanfaat guna menentukan strategi vaksinasi COVID-19 kedepannya, seperti perlu tidaknya dosis ketiga untuk populasi yang rentan.
Meskipun imunitas alami terlihat menunjukkan proteksi yang lebih kuat dan bertahan lama, penyintas COVID-19 tetap disarankan untuk menerima vaksinasi dengan regimen lengkap untuk mencapai tingkat kekebalan yang lebih tinggi.
Studi populasi lebih lanjut perlu dilakukan untuk menilai tingkat infeksi pada individu yang mendapatkan vaksin COVID-19, penyintas COVID-19, dan kombinasi keduanya. Luaran yang ada di dunia nyata, seperti kebutuhan hospitalisasi, kebutuhan perawatan intensif, dan mortalitas perlu diteliti pada studi tersebut.