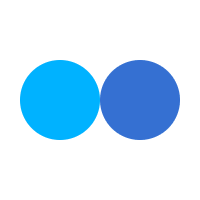Bukti dari studi terkinis mendukung rekomendasi untuk stop atau menghentikan premedikasi transfusi darah, sebab premedikasi justru berpotensi menyebabkan efek samping serta menambah biaya.
Penggunaan premedikasi pada transfusi darah masih banyak diterapkan di berbagai pusat pelayanan medis. Premedikasi yang diberikan biasanya adalah paracetamol dan antihistamin, seperti diphenhydramine. Pemberian premedikasi ini diharapkan dapat mencegah terjadinya reaksi transfusi yang mungkin terjadi akibat pemberian produk darah maupun komponen darah pada pasien.
Meski digunakan secara luas, penggunaan premedikasi lebih berdasarkan pada pengalaman saja, dan tidak berbasis bukti klinis. Efektivitasnya dalam mencegah reaksi transfusi belum diketahui secara pasti.
Reaksi Transfusi
Reaksi transfusi dibagi menjadi dua kelompok, yaitu imunologik dan nonimunologik. Reaksi transfusi imunologik terbagi lagi menjadi reaksi cepat dan lambat, dimana reaksi imunologik cepat terdiri atas reaksi transfusi hemolitik imun, reaksi demam nonhemolitik (febrile non-hemolytic transfusion reaction/FNHTR), reaksi alergi (allergic transfusion reaction/ATR), dan injuri paru akut terkait transfusi (transfusion related acute lung injury/TRALI).
Reaksi transfusi nonhemolisis akut memiliki angka kejadian bervariasi, hingga 38% dari seluruh transfusi trombosit dan sel darah merah. Di antara reaksi transfusi tersebut, demam nonhemolisis dan alergi merupakan yang paling sering terjadi.[1,2]
Reaksi Demam Nonhemolitik (Febrile Non-Hemolytic Transfusion Reaction/ FNHTR)
Demam nonhemolisis akibat reaksi transfusi didefinisikan sebagai peningkatan suhu tubuh ≥1o C di atas baseline dan/atau menggigil dalam periode 3 jam transfusi. Demam dapat muncul pada awal transfusi hingga beberapa jam setelah transfusi selesai. Pada umumnya, FNHTR dapat ditangani dengan pemberian paracetamol dan mengalami resolusi dalam beberapa jam.[2,3]
Dalam penelitian, angka kejadian FNHTR bervariasi pada transfusi sel darah merah dan trombosit. Pada transfusi trombosit, angka kejadian FNHTR bervariasi antara 0.09% hingga >27%. Sementara angka kejadian FNHTR pada transfusi sel darah merah diperkirakan sekitar 0,33%.[2]
Patofisiologi terjadinya FNHTR masih belum diketahui secara pasti, namun diperkirakan demam terjadi melalui dua mekanisme berbeda yaitu pertama, akibat interaksi antara antibodi sitotoksik resipien dengan antigen spesifik donor, dan kedua akibat proses penyimpanan trombosit yang menyebabkan pengeluaran sitokin aktif oleh residu leukosit.[4]
Pada mekanisme pertama, kompleks antigen antibodi yang terbentuk akan merangsang sitokin yang berperan sebagai pirogen endogenik yang menimbulkan demam. Sitokin yang berkaitan diantaranya adalah interleukin (IL)-β, IL-6, dan tumor necrosis factor (TNF)-α.[4]
Reaksi Alergi (Allergic Transfusion Reaction/ ATR)
Reaksi alergi didefinisikan sebagai munculnya urtikaria, pruritus, mengi, hingga angioedema dalam periode beberapa jam transfusi. Reaksi alergi bervariasi, mulai dari ringan hingga berat. Reaksi alergi ringan dapat berupa urtikaria yang muncul pada badan dan ekstremitas, sementara reaksi alergi berat dapat berupa mengi, sesak, hipotensi, takikardia hingga syok anafilaktik dan kematian. Reaksi alergi akibat transfusi yang tersering berupa reaksi ringan dan mudah ditatalaksana.[2,3]
Reaksi alergi seperti yang diketahui merupakan reaksi hipersensitivitas tipe I yang melibatkan antibodi IgE yang berinteraksi dengan antigen. Antibodi IgE akan berikatan dengan reseptor pada sel mast dan basofil. Sel mast akan mengeluarkan berbagai mediator yang akhirnya menyebabkan gejala klasik alergi seperti urtikaria, edema, produksi mukus, konstriksi saluran napas, dan mengi.[2,4]
Munculnya reaksi transfusi, baik berupa demam maupun alergi, hingga kini tidak dapat diprediksi. Pada prakteknya, sulit pula untuk membedakan gejala reaksi transfusi ringan dengan gejala akibat penyakit utama yang diderita pasien misalnya sepsis.
Oleh karena itu, penanganan pertama pada gejala reaksi transfusi adalah dengan terminasi transfusi, kecuali untuk gejala alergi urtikaria ringan, transfusi masih dapat dilanjutkan. Pada pasien dengan riwayat reaksi transfusi, pemberian produk darah aferesis dari donor tunggal dan produk darah leukoreduksi disertai premedikasi dapat menjadi pilihan.[4,5]
Premedikasi pada Transfusi Darah
Penggunaan premedikasi pada transfusi darah telah banyak diterapkan secara luas sejak tahun 1950. Pemberian premedikasi pada transfusi darah diharapkan dapat mencegah reaksi transfusi yang mungkin terjadi akibat pemberian produk darah dari donor ke resipien.[1-3]
Di Amerika Serikat dan Kanada, paracetamol dan diphenhydramine merupakan dua obat tersering yang digunakan sebagai premedikasi untuk mencegah reaksi demam nonhemolitik dan reaksi alergi. Dua obat ini digunakan sebanyak 50–80% dalam premedikasi pada transfusi darah.
Dalam studi dengan 7.900 transfusi, sebanyak 13% subjek menggunakan premedikasi paracetamol saja, 16% subjek mendapatkan premedikasi diphenhydramine saja, sementara hingga 38% subjek mendapat premedikasi berupa kombinasi keduanya. Faktor yang menentukan subjek mendapat premedikasi atau tidak adalah riwayat penggunaan premedikasi sebelumnya yang tercatat pada rekam medis.[2]
Bahkan, sebuah survei informal menyatakan praktisi kesehatan biasanya hanya mengikuti riwayat premedikasi yang tercatat dalam rekam medis tanpa mempertanyakan mengapa obat tersebut diperlukan. Hal ini menunjukkan penggunaan premedikasi sebagai profilaksis lebih dititikberatkan pada kebiasaan, dan bukan bukti ilmiah.[2]
Paracetamol dipilih sebagai premedikasi untuk efek antipiretiknya. Namun, penggunaan paracetamol jangka panjang serta dosis tinggi dapat bersifat hepatotoksik. Sedangkan diphenhydramine merupakan golongan antihistamin yang biasa digunakan pada reaksi alergi. Efek samping diphenhydramine berupa efek antikolinergik, gangguan atensi, memori, psikomotor, dan delirium karena dapat menembus sawar darah otak.[2,4]
Penggunaan diphenhydramine rutin dan tidak rasional dikhawatirkan dapat menyebabkan efek yang serius terhadap fungsi sistem saraf pusat yang berujung pada penurunan kualitas hidup.[4]
Premedikasi Tidak Efektif untuk Mencegah Reaksi Transfusi
Meskipun telah digunakan secara luas, efektivitas premedikasi untuk mencegah reaksi transfusi belum banyak diuji secara langsung. Dalam uji klinis terandomisasi yang dilakukan oleh Kennedy et al. tahun 2008, penggunaan premedikasi tidak menunjukkan hasil yang berbeda dibandingkan plasebo dalam menurunkan angka kejadian reaksi demam nonhemolitik.[1]
Uji retrospektif yang dilakukan Sanders et al. pada tahun 2005 bertujuan untuk menilai efektivitas premedikasi dalam menurunkan angka kejadian FNHTR dan reaksi alergi pada pasien pediatrik. Uji tersebut mendapatkan penggunan premedikasi tidak menyebabkan perbedaan signifikan pada kejadian FNHTR dan reaksi alergi, dibandingkan tanpa pemberian premedikasi.[6]
Sebuah tinjauan sistematis dan metaanalisis oleh Ning et. al. pada tahun 2019 juga mengonfirmasi temuan tersebut. Kejadian reaksi transfusi nonhemolitik tidak berbeda bermakna pada kelompok premedikasi dengan kelompok yang menerima plasebo atau tanpa terapi apapun. Manfaat penggunaan premedikasi pada pasien dengan riwayat reaksi transfusi juga tidak diketahui dengan pasti, dan membutuhkan uji klinis lebih lanjut.[7]
Studi oleh Savage et al. pada tahun 2016 mendapatkan bahwa pemberian premedikasi sebelum transfusi apheresis platelet tidak memiliki hubungan bermakna dengan allergic transfusion reaction (ATR). Premedikasi yang diteliti adalah difenhidramin, antagonis reseptor H2, seperti ranitidin dan famotidin, dan glukokortikoid, misalnya dexamethasone.[8]
Implikasi Klinis
Melihat dari hasil penelitian di atas, dokter sebaiknya berhenti memberikan premedikasi sebelum transfusi darah, mengingat risiko efek samping dari premedikasi. Pada pasien dengan penyakit berat, seperti sepsis, maupun pasien dengan risiko kegagalan multiorgan, premedikasi juga akan memperberat kerja hati sehingga meningkatkan risiko morbiditas.[2]
Selain risiko efek samping, penggunaan premedikasi juga meningkatkan pengeluaran biaya yang tidak perlu bagi pasien. Hal ini terutama dirasakan penderita penyakit kronik, seperti thalassemia beta mayor, yang membutuhkan transfusi rutin seumur hidupnya.
Pada pasien dengan riwayat reaksi transfusi, baik sekali maupun lebih dari sekali, penggunaan premedikasi untuk mencegah reaksi transfusi juga tidak terbukti bermanfaat. Pasien dengan riwayat reaksi transfusi dapat menggunakan alternatif yang disarankan, yaitu transfusi menggunakan produk sel darah merah cuci (washed packed red cell) atau produk leukoreduksi untuk mengurangi risiko reaksi transfusi berulang.[6]
Kesimpulan
Penggunaan premedikasi pada transfusi darah hingga kini belum terbukti efektif untuk mencegah reaksi transfusi. Di sisi lain, terdapat risiko efek samping, morbiditas, dan peningkatan biaya yang tidak perlu akibat penggunaan premedikasi ini.
Sebaiknya, stop pemberian premedikasi sebelum transfusi. Pada pasien dengan riwayat reaksi transfusi, gunakan alternatif yang disarankan, yaitu transfusi menggunakan produk sel darah merah cuci (washed packed red cell) atau produk leukoreduksi.
Direvisi oleh: dr. Livia Saputra