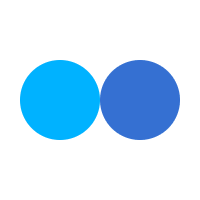Pendahuluan Clostridium Difficile Colitis
Clostridium difficile colitis atau yang dikenal juga sebagai Clostridioides difficile colitis adalah kondisi peradangan pada kolon yang disebabkan oleh infeksi bakteri Clostridium difficile sehingga menyebabkan terjadinya diare akut dan gejala gastrointestinal lainnya. Pada tahun 2016 Clostridium difficile ini berubah nama menjadi Clostridioides difficile, namun hingga saat ini masih dikenal sebagai Clostridium difficile. Infeksi bakteri ini merupakan penyebab utama dari diare nosokomial di seluruh dunia.[1-3]
Clostridium difficile merupakan bakteri penghasil spora, gram positif, anaerob, yang dapat memproduksi toksin, yaitu enterotoksin A (toksin A) dan sitotoksin B (toksin B). Transmisi dari infeksi ini terjadi secara fekal-oral dengan menelan spora dari C. difficile. Clostridiosis memiliki manifestasi klinis yang bervariasi, mulai dari asimtomatik (karier), diare derajat ringan-sedang, hingga kolitis fulminan yang dapat mengancam nyawa.[1,2]
Terdapat dua faktor risiko utama terjadinya infeksi ini, yaitu penggunaan antibiotik jangka panjang dan paparan terhadap bakteri C. difficile. Selain itu, risiko infeksi juga lebih besar pada lansia dan pasien dengan riwayat rawat inap yang sering atau lama. Faktor risiko lainnya berupa kondisi komorbid seperti inflammatory bowel disease, riwayat pembedahan saluran pencernaan, kanker, gagal ginjal kronis, dan penggunaan imunosupresan.[1-3]
Diagnosis Clostridium difficile colitis dapat diperkirakan pada pasien yang mengalami diare dan sedang dalam pengobatan antibiotik selama 3 bulan terakhir, baru saja menjalani rawat inap di rumah sakit, dan/atau mengalami diare dalam 48 jam atau lebih saat sedang dirawat inap di rumah sakit. Diagnosis dapat dikonfirmasi dengan mengkombinasikan dua jenis pemeriksaan.
Pemeriksaan pertama disarankan yang memiliki nilai prediksi negatif yang tinggi, misalnya Glutamate Dehydrogenase (GHD) dengan metode Enzyme Immunoassay (EIA) atau Nucleic Acid Amplification Test (NAAT). Sedangkan pemeriksaan kedua disarankan yang memiliki nilai prediksi positif yang tinggi, yaitu pemeriksaan toksin A/B pada feses dengan metode EIA.[1,2,4]
Penatalaksanaan infeksi Clostridium difficile mencakup berbagai aspek, mulai dari penghentian penggunaan antibiotik, melakukan isolasi terhadap pasien, dan memberikan terapi antibiotik sesuai dengan derajat beratnya infeksi. Pasien clostridiosis yang asimtomatik tidak perlu untuk diberikan tatalaksana.
Metronidazole per oral menjadi antibiotik lini pertama pada clostridiosis derajat ringan-sedang. Vancomycin menjadi lini pertama pada clostridiosis derajat berat. Namun,sediaan oral obat ini tidak tersedia di Indonesia.
Pada tahun 2017, pedoman Infectious Diseases Society of America (IDSA) merekomendasikan bahwa vancomycin atau fidaxomicin per oral lebih dianjurkan sebagai terapi awal infeksi C. difficile daripada metronidazole. Namun, pada tahun 2021, IDSA mengedepankan pemberian fidaxomicin dibandingkan vancomycin. Meski begitu, ketersediaan kedua obat ini masih terbatas di Indonesia. Dalam kasus ini, IDSA merekomendasikan untuk menggunakan metronidazole sebagai tatalaksana infeksi C. difficile derajat ringan.
Pada pedoman ini juga tidak disarankan penggunaan jangka panjang metronidazole atau berulang kali, mengingat risiko neurotoksisitas (strong recommendation, moderate quality of evidence). Vancomycin per oral maupun fidaxomicin tidak tersedia secara luas di Indonesia, sehingga metronidazole tetap menjadi antibiotik lini pertama.[1-3,5]